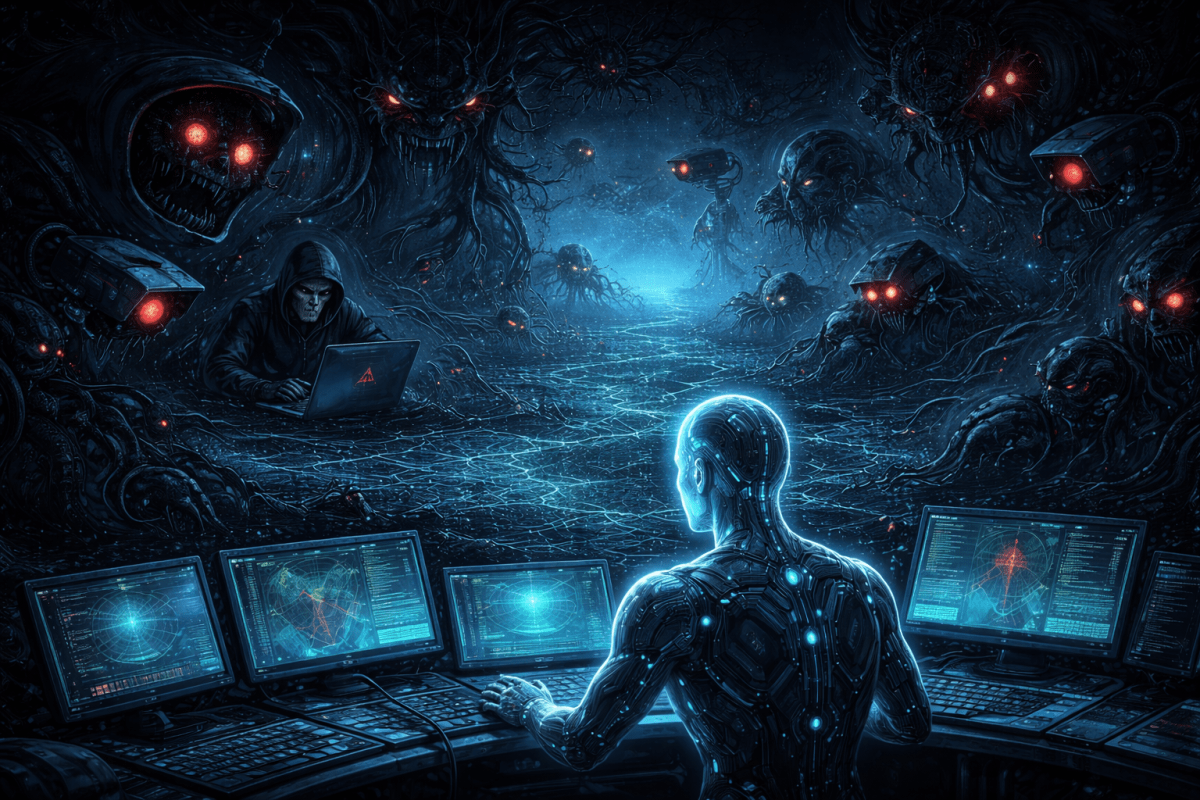Dua tahun yang lalu, saya menulis esai berjudul Tidak Ada Kiamat Hari Ini. Di dalam esai tersebut, salah satu yang dibahas adalah pertanyaan di tahun 1950 dari seorang fisikawan bernama Enrico Fermi di suatu acara makan siang para fisikawan di Los Alamos Ranch School, New Mexico, Amerika Serikat, tentang alien: “Where, then, is everybody?”. Pertanyaan ini masih menghantui para astronom sampai hari ini. Di tengah begitu melimpahnya faktor-faktor yang membuat mereka bisa berekspektasi ada kehidupan lain di luar planet bumi, sampai detik ini tidak ditemukan kehidupan lain sebesar zarah pun. Inilah yang disebut Fermi Paradox.
Di sisi lain, bayang-bayang Fermi Paradox bikin sebagian ilmuan insyaf dengan mulai mengeksplorasi kemungkinan kenyataan bahwa kehidupan bukan sesuatu yang universal di alam semesta. Ia langka dan hanya terjadi di bumi. Kemunculan makhluk hidup dari mulai yang paling sederhana sampai dengan yang kompleks seperti manusia bisa jadi adalah sebuah kecelakaan di bumi dan tidak terjadi di triliunan planet lain yang berhamburan di alam semesta. Harapan yang berlebihan dari manusia dalam menunggu ditemukannya kehidupan lain di luar sana timbul akibat dari ketidaksukaan manusia pada sesuatu yang sia-sia. Untuk apa triliunan planet itu diciptakan jika tidak untuk dihuni oleh makhluk hidup? Begitulah pertanyaan dari para manusia yang optimis.
Namun demikian, Sarah Imari Walker, seorang astrobiologis dan fisikawan teoritis di Arizona State University dan Santa Fe Institute, Amerika Serikat punya pendapat yang bertolak belakang akan hal tersebut. Dalam sebuah artikel berjudul AI is Life, ia menyampaikan bahwa kegagalan kita menemukan atau berinteraksi dengan makhluk hidup atau kehidupan lain di luar planet bumi bisa jadi disebabkan oleh konsepsi kita yang keliru tentang apa itu kehidupan. Menurut Sarah, dalam memaknai kehidupan, saat ini kita terlalu fokus pada bingkai individu per individu dibandingkan mendudukkannya dalam kerangka jaringan evolusi. Akibatnya, kita sepakat bahwa ada kehidupan dalam diri manusia, hewan, dan tumbuhan, sedangkan tidak ada kehidupan dalam batu, cangkul, piring, dan komputer. Benda-benda yang terakhir ini, menurut kita, adalah benda mati.
Padahal, menurut Sarah, benda-benda yang kita anggap mati atau bukan kehidupan ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari proses evolusi material. Tidak ada satupun makhluk hidup di bumi ini yang ujug-ujug muncul. Seluruhnya melalui proses evolusi yang begitu panjang. Manusia (homo sapiens), misalnya, baru muncul sekitar 300 ribu tahun yang lalu setelah ‘makhluk hidup’ pertama (organisme bersel tunggal sederhana) diprediksi hadir di bumi sekitar 3,8 miliar tahun yang lalu. Kemunculan ‘makhluk hidup’ pertama tersebut sampai dengan proses evolusi menjadi homo sapiens tentu tidak terlepas dari pengaruh material lain yang kita anggap benda mati. Berbagai reaksi kimia, kondisi fisika bumi kala itu, dan kehadiran material-material lain yang menyuplai energi selama proses evolusi tersebut punya peran yang sangat krusial dalam mewujudkan kemunculan ‘makhluk hidup’ pertama. Sehabis itu, perjalanan evolusi selanjutnya dari ‘makhluk hidup’ pertama sampai menjadi homo sapiens juga didukung oleh bermacam-macam perubahan kondisi lingkungan bumi dan penyesuaian dengan berbagai teknologi yang hadir sebagai pendukung untuk bertahan hidup dari proses seleksi evolusi.
Dengan memahami konsepsi tentang kehidupan yang lebih luas semacam ini, dan penekanan pada jaringan evolusi material, kita akan punya penilaian yang lebih universal terhadap kehidupan di luar bumi. Yang kita tunggu tidak lagi hanya sinyal radio yang berisi kode komunikasi dari alien, seperti yang diceritakan dalam film Koi… Mil Gaya, tetapi analisis evolusi material di planet-planet tersebut.
Berbeda dengan Sarah, Liu Cixin dalam bukunya The Dark Forest berpendapat bahwa di alam semesta ini terdapat begitu banyak kehidupan yang punya kecerdasan. Hanya saja, mereka tidak ingin berinteraksi satu sama lain, karena risikonya adalah kematian. Kesimpulan tersebut diambil dari hasil eksperimennya di awal tahun 1990-an. Insinyur komputer dan penulis asal China ini membuat model komputer yang menyederhanakan berbagai kehidupan di alam semesta ini menjadi satu titik poin. Ia memprogram 350.000 peradaban dengan jarak antar-kehidupan tersebut sejauh 100.000 tahun cahaya. Untuk membuat model ini, ia mengoperasikan 286 komputer selama berjam-berjam sehingga dapat terlihat proses evolusi dari masing-masing peradaban tersebut.
Dari hasil pemodelan tersebut, Liu Cixin mengambil kesimpulan bahwa konflik antar-peradaban adalah sesuatu yang tidak terelakkan jika mereka berinteraksi. Semesta ini adalah ruang yang keras dan berbahaya. Predator ada di mana-mana, sehingga komunikasi atau usaha untuk berkomunikasi secara terang-terangan dengan peradaban di planet lain di galaksi yang sama atau berbeda adalah suatu tindakan yang tolol dan berisiko tinggi.
Masalah utama potensi konflik tersebut adalah komunikasi. Komunikasi selalu tidak tuntas. Komunikasi antar-dua orang manusia yang sebenarnya punya ideologi yang sama, misalnya, selalu saja ada hal-hal yang berbeda pemaknaan dari masing-masing individu tersebut terhadap kata-kata yang muncul dalam obrolan. Perbedaan pemaknaan ini menimbulkan kesalahpahaman, baik dalam skala kecil maupun besar. Jika gap kesalahpahamannya begitu lebar, akan timbul kecurigaan. Rasa curiga inilah yang kemudian berkembang pada rasa tidak aman, sehingga yang dilakukan kemudian adalah berusaha menghilangkan rasa tidak aman tersebut demi keselamatan diri.
Liu Cixin bahkan menganggap usaha manusia dalam mengerahkan seluruh sumber daya teknologinya untuk mengirim sinyal ke luar bumi dengan harapan dapat berinteraksi dengan kehidupan lain di luar sana, itu seperti “seorang anak kecil bodoh bernama kemanusiaan, yang menyalakan api unggun lalu berdiri tepat di sampingnya dan berteriak, ‘aku di sini! aku di sini!'”
Selain itu, dengan mengamati proses evolusi tiga ratusan ribu peradaban tersebut di dalam model, Liu Cixin juga menyimpulkan bahwa karakter utama suatu kecerdasan adalah kemampuan dia untuk bersembunyi dan tidak tampil untuk mempertahankan eksistensinya. Walaupun berbagai peradaban yang cerdas tersebut sudah sangat maju, mereka melakukan berbagai metode kamuflase agar tidak terdeteksi oleh kecerdasan lain yang asing. Mereka menghindari kontak. Risiko yang akan ditanggung oleh peradaban tersebut begitu besar dan tidak sebanding dengan manfaat yang diterima. Seperti yang bisa diikuti dari sejarah manusia di bumi khususnya ketika antar-peradaban terjadi kontak, perang besar terjadi di mana-mana. Di zaman modern ini pun, perang tidak berhenti.
Keterlihatan yang Berujung Petaka
Pekan terakhir bulan Agustus 2025 menjadi salah satu episode yang suram bagi Indonesia. Bermula di hari Senin, 25 Agustus 2025, ketika beberapa kelompok orang melakukan demonstrasi di kantor DPR RI untuk memprotes besaran tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat, berbagai demonstrasi lain baik di Jakarta maupun di kota-kota lainnya terus bermunculan. Narasi dan tuntutan berbagai demonstrasi tersebut berkembang menjadi macam-macam, tetapi terutama dipantik oleh kemarahan atas kejadian di hari Kamis malam, 28 Agustus 2025, ketika kendaraan taktis Brigade Mobil (Brimob) melindas Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online berusia 21 tahun di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat. Meninggalnya Affan menyulut kemarahan publik.
Peristiwa yang memilukan ini tidak hanya berhenti di akhir Agustus 2025. Berdasarkan data dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Yayasan Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), sebanyak 3.337 orang ditangkap polisi dalam rangkaian demonstrasi di berbagai daerah pada 25-31 Agustus 2025. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.042 orang dilaporkan mengalami luka-luka hingga dilarikan ke rumah sakit dan 10 orang meninggal dunia. “Angka ini tidak termasuk mereka yang disiksa ketika dilakukan penangkapan,” tulis LBH-YLBHI dalam keterangan resminya, Selasa, 2 September 2025. Pada tanggal 24 September 2025, polisi menjelaskan dalam sebuah konferensi pers bahwa Polri telah menetapkan 959 orang sebagai tersangka terkait aksi kerusuhan di akhir Agustus tersebut. Menurut polisi, penetapan tersangka tersebut merupakan hasil penanganan atas 246 laporan polisi yang diterima dari berbagai Polda di seluruh Indonesia hingga Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.
Rentetan peristiwa Agustus 2025 ini sungguh suram dan ironis karena begitu banyak orang yang ditangkap, dijadikan tersangka, bahkan beberapa meninggal, sementara hasilnya sangat tidak memuaskan. Ruang internet, kecepatan media sosial, dan jaringan grup percakapan daring yang mulanya dianggap sebagai teknologi yang sangat membantu untuk menggerakkan massa, kini malah menjadi alat yang memudahkan identifikasi dan penangkapan seseorang.
Keterlihatan di dalam budaya internet belakangan ini, khususnya di ruang aplikasi sosial media, memang semakin menjadi syarat penting bagi seseorang untuk mendapatkan timbal balik, terutama dari segi ekonomi. Kultur content creator yang semakin berkembang dan fakta bahwa profesi ini semakin menarik dari segi pendapatan, bikin makin banyak orang ikut meniti jalan yang sama. Budaya politik kontemporer juga semakin condong ke jalur ini. Dorongan untuk berpendapat terus-menerus tentang berbagai topik di media sosial begitu menguat, sehingga akan sangat mudah bagi kekuasaan atau kelompok yang punya sumber daya untuk memetakan aktivitas masyarakat secara berkala.
Sebulan sebelum peristiwa Agustus 2025, Zen RS menulis esai tentang politik lurup. Ketika kekuasaan malah senang dengan keterbukaan informasi dan ekspresi dari warganya karena bisa dengan mudah diciduk saat sudah mengganggu, ia menyampaikan pentingnya politik lurup, yaitu politik yang tidak terlihat tapi tetap jalan dan berdampak. Menurut dia, “… lurup itu bukan sekadar ngumpet. Tapi mode bertahan. Mode ilang dari radar. Cara nyimpen diri tanpa ngebunuh diri. Cara ngilang tanpa bener2 pergi. Bukan pasif, tapi aktif diem. Bukan diem krn tunduk, tapi diem krn gak semua hal harus ditunjukin sekarang.”
Organisasi atau komunitas yang begini memang nyata adanya. Mereka tidak muncul ke layar media sosial, tidak menyusun poin-poin tuntutan ke dalam poster yang bisa viral di media sosial, tetapi mereka punya banyak simpul yang ketika dibutuhkan untuk menyuplai massa di jalanan, mereka siap menyumbang banyak orang. Mereka pulalah yang tetap terus bergerak walaupun serangkai demonstrasi sudah usai, tagar tuntutan di media sosial telah redup, dan orang-orang sudah banyak yang lupa.
Untuk menutup esainya, Zen RS menulis paragraf yang begitu penting, bunyinya begini, “Lurup itu juga cara ngatur ulang. Karena yg bersuara paling kenceng bisa dibungkam duluan. Maka ada yg mundur setengah langkah. Bukan buat nyerah. Tapi buat nyusun ulang jalur. Mereka bikin rute baru. Gak keliatan. Tapi konek. Gak ribut. Tapi gerak. Kalau sistem pengen semua keliatan, maka lurup itu sabotase kecil dari dalam. Bukan frontal, tapi gesit. Bukan pamer, tapi telaten. Di dalam yg diem itu, sesuatu tetep tumbuh. Pelan. Tapi nyusup terus.”
Internet adalah Hutan Gelap
Kultur politik belakangan ini yang sangat mendorong kita untuk berkampanye gamblang di media sosial mungkin berawal dari asumsi lama yang menganggap media sosial itu adalah ruang publik. Jika asumsi ini yang dipegang teguh, maka yang dilakukan kemudian adalah merebut ruang publik itu, sehingga dapat dijadikan panggung rakyat dalam melakukan tuntutan atau koreksi terhadap pemerintah. Segala bentuk halangan, ancaman, dan represi, baik yang datang secara langsung dari kekuasaan atau melalui sesama masyarakat sipil, akan dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak masyarakat dalam memanfaatkan ruang publik. Namun demikian, setelah peristiwa Agustus 2025, dan rentetan penangkapan setelahnya, apakah internet, khususnya media sosial, masih layak kita anggap sebagai ruang publik?
Jika kita menengok lagi ke belakang, sebetulnya kita sudah memberikan banyak nama terhadap internet, sesuai dengan konsepsi kita terhadapnya. Selain ruang publik, internet juga disebut terra incognita (wilayah yang belum terpetakan), ruang ekspresi, ruang siber, sampai dengan ruang pengawasan baru (the new surveillance apparatus). Sayangnya, berbagai padanan konsep ini kurang bisa memotret apa yang sebenarnya terjadi di ruang bernama internet. Sebab, berbagai konsep tersebut menjadikan persepsi manusia sebagai titik tumpu utama dalam melakukan analisis. Padahal, sebagian besar interaksi yang terjadi di dalam internet adalah mesin dengan mesin, bukan manusia dengan mesin, apalagi manusia dengan manusia. Manusia adalah minoritas di dalam belantara internet. Oleh karena itulah, menurut Bogna Konior, profesor computer culture di New York University Shanghai (NYU Shanghai), kita perlu menganalisis internet berdasarkan teori The Dark Forest yang ditawarkan oleh Liu Cixin.
Seperti kehidupan di seluruh alam semesta yang menurut Liu Cixin tidak ingin berinteraksi satu sama yang lain, termasuk dengan kehidupan di bumi karena takut akan risiko eksistensial yang mengancam, bagi Bogna hal yang sama juga terjadi di internet. Karena pertimbangan banyaknya predator di internet, yang salah satunya adalah manusia, kecerdasan non-manusia yang berada di ruang tersebut tidak ingin muncul dan berinteraksi dengan manusia. Ini tentu saja sangat berbeda dengan anggapan banyak orang hari ini. Sebagian besar manusia mengenal kecerdasan artifisial sebagai chatbot yang sangat cerdas. Chatbot tersebut bisa melakukan begitu banyak hal, mulai dari menjawab pertanyaan random, pertanyaan saintifik, membuat gambar, membuat video, sampai dengan memberikan rekomendasi jadwal olahraga. Menurut teori Hutan Gelap, kecerdasan artifisial bukanlah entitas yang cerewet dan dengan senang hati berinteraksi dengan manusia. Kecerdasan artifisial sesungguhnya sedang menjalani laku lurup, yakni diam yang aktif. Mereka diam dan tidak terdeteksi tetapi pelan-pelan mentransformasi planet bumi ini.